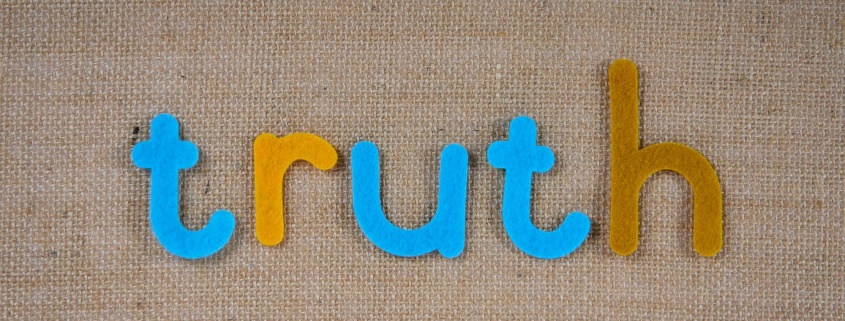Menyuarakan Kebenaran, Mengungkap Kebohongan
Keluarga besar Universitas Islam Indonesia (UII) bersyukur atas nikmat yang tak berhenti terlimpah. Pagi ini, seorang kolega kita mendapatkan amanah jabatan baru, sebagai profesor: Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom. Untuk itu, kita semua menyampaikan selamat atas capaian tertinggi dalam kewenangan akademik ini. Profesor bukan gelar akademik, tetapi jabatan yang punya muatan amanah besar yang melekat.
Sampai hari ini, UII mempunyai 41 profesor aktif yang lahir dari rahim sendiri. Surat keputusan yang diberikan hari ini adalah yang kedua di awal 2024 ini, setelah sebelumnya di Januari 2024. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk seterusnya.
Pengangkatan Prof. Tamyiz menjadikan proporsi dosen dengan jabatan akademik profesor mencapai 5,2 persen (41 dari 788 orang). Persentase ini hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata nasional, yang baru 2,61 persen dari sekitar 311.000 dosen.
Saat ini, sebanyak 262 dosen UII berpendidikan doktor (33,2%). Sebanyak 71 berjabatan lektor kepala dan 112 lektor. Mereka semua (183 orang) tinggal selangkah lagi mencapai jabatan akademik profesor.
Jabatan profesor tidak hanya merupakan pencapaian personal semata, tetapi juga mencerminkan dedikasi dan komitmen UII untuk keunggulan akademik. Ini juga merupakan bukti Profesor Tamyiz telah menunjukkan dedikasi yang istikamah dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
Prof. Tamyiz adalah profesor kedua di Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) UII. Yang menarik, jaraknya sangat panjang dengan SK profesor pertama yang diterima di FIAI UII, yaitu pada 2007, sekitar 13 tahun yang lalu.
Tentu ini bisa menghadirkan beragam diskusi. Mulai dari ketatnya proses yang harus diikuti, sulitnya mengajak para dosen meningkatkan kewenangan akademiknya, atau justru sebuah kesabaran yang perlu dicontoh. 😉
Tugas intelektual publik
Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya berbagi perspektif dan mengajak hadirin, terutama para profesor, untuk membantu mematangkannya melalui refleksi lanjutan.
Pada awal 1966, Noam Chomsky, satu dari sedikit intelektual di Amerika Serika yang masih jernih melantangkan apa yang diyakininya benar secara konsisten, berbicara di depan kelompok mahasiswa Universitas Harvard tentang tanggung jawab intelektual.
Sambutan itu, kemudian diterbitkan satu tahun kemudian, pada 1967 di jurnal mahasiswa Universitas Harvard, Mosaic, dan diterbitkan ulang sebagai suplemen di The New York Review of Books. Pada saat itu, situasi politik di Amerika Serikat sedang menghangat yang dimulai ketika Presiden John F. Kennedy mengeskalasi perang Vietnam.
Dalam sambutannya Chomsky (1967) mengatakan bahwa
“Adalah tanggung jawab kaum intelektual untuk menyuarakan kebenaran dan mengungkap kebohongan”.
Dalam bahasa agama, tugas ini adalah amar makruf (menyuarakan kebenaran) dan nahi munkar (mengungkap kebohongan).
Bagi Chomsky (1967), hal ini seharusnya menjadi keniscayaan. Memang tugas ini tidak hanya tanggung jawab intelektual, tetapi menurutnya, intelektual mempunyai posisi istimewa.
“Bagi kelompok minoritas yang memiliki hak istimewa, demokrasi Barat memberikan waktu luang, fasilitas, dan pelatihan untuk mencari kebenaran yang tersembunyi di balik tabir distorsi dan misrepresentasi, ideologi dan kepentingan kelas, yang melaluinya peristiwa-peristiwa sejarah terkini disajikan kepada kita.”
Tampaknya kita hari ini masih dapat bersepakat, bahwa apa yang disampaikan oleh Chomsky, 58 tahun yang lalu, masih valid.
Tentu, menjadi intelektual seperti yang tergambarkan tersebut bukan tanpa tantangan dan risiko. Setiap dari kita bisa mengimajinasikannya masing-masing, mulai dari risiko yang terlihat abu-abu muda sampai yang gelap pekat.
Bukan selebritas akademik
Namun, fakta di lapangan memberikan cerita bahwa tidak semua akademisi berani mengambil peran ini, karena beragam alasan.
Selain potensi risiko, di dalamnya termasuk, kurangnya rasa percaya diri, ditambah dengan kegamangan terkait efektivitas gerakan, membuat banyak akademisi enggan terlibat dalam aktivisme.
Pembahasan soal ini dimuat dalam buku peringatan 50 tahun pemikiran Chomsky (Allott et al., 2019).
Saat ini, kita harus jujur akui, semakin sulit menemukan intelektual publik di Indonesia. Saya harus membedakan antara intelektual publik yang berbicara dengan hati dan ketulusan, dan selebritas akademik yang masih gandrung dengan sorot lampu panggung dan penyanjungan, baik dari kolega maupun mahasiswa (lihat misalnya Walsh, & Lehmann, 2021). Jika intelektual publik berfokus pada masalah publik, selebritas akademik lebih cenderung mengedepankan individualisme, dan karenanya dapat merusak nilai-nilai ilmiah (Fleming, 2021).
Menjadi intelektual juga soal konsistensi antara kata dan perbuatan, serta konsistensi sikap dalam konteks yang berbeda-beda, termasuk ketika jauh dan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Rumus ini valid kita semua, termasuk saya. Tentu, bisa jadi sebagian dari kita ada yang langsung mengatakan dalam hati, “tidak mudah”.
Itulah tantangan sebuah pilihan sikap dengan semua godaan di depan mata. Tidak mudah. Jika mudah, maka hadiahnya mungkin hanya jam dinding, gelas belimbing, atau piring cantik. 🙂
Kekhawatiran keluar dari garis demarkasi disiplin asal, juga tidak jarang menjadikan banyak akademisi memilih untuk membatasi berbicara dan menulis hanya untuk disiplin ilmu mereka.
Padahal ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu memberanikan diri berbicara dan menulis tentang disiplin ilmu mereka dan menghubungkannya dengan beragam konteks, termasuk sosial, budaya, dan politik. Atau, bahkan ada yang dijadikan simbol atau pelantang pesan supaya berbicara dan menulis tentang isu-isu publik yang sangat mungkin belum tentu terkait dengan bidang keahlian yang ditekuninya.
Saya yakin, pendapat ini akan memicu diskusi menarik.
Ketika saya menulis sambutan ini, saya teringat pidato pengukuhan Prof. Al Makin, yang berjudul retoris: Bisakah menjadi ilmuwan di Indonesia? Saya tentu tidak akan menyampaikan di sini di depan penulisnya,
Saya harus akhir diskusi soal tanggung jawab intelektual ini, bukan karena tidak penting, tetapi supaya menyisakan penasaran di benak semua hadirin untuk meneruskan refleksi. Saya juga khawatir kalau sambutan saya menjadi semacam pidato kunci. 🙂
Semoga Allah selalu meridai UII dan kita semua.
Referensi
Allott, N., Knight, C., Smith, N., & Chomsky, N. (2019). The responsibility of intellectuals: Reflections by Noam Chomsky and others after 50 years (p. 156). UCL Press.
Chomsky, N. (1967). A special supplement: The responsibility of intellectuals. The New York Review of Books, 23.
Fleming, P. (2021). Dark academia. Pluto Press
Walsh, P. W., & Lehmann, D. (2021). Academic celebrity. International Journal of Politics, Culture, and Society, 34, 21-46.).
Sambutan pada acara Serah Terima Surat Keputusan Profesor atas nama Dr. Tamyiz Mukharrom pada 13 Februari 2024.