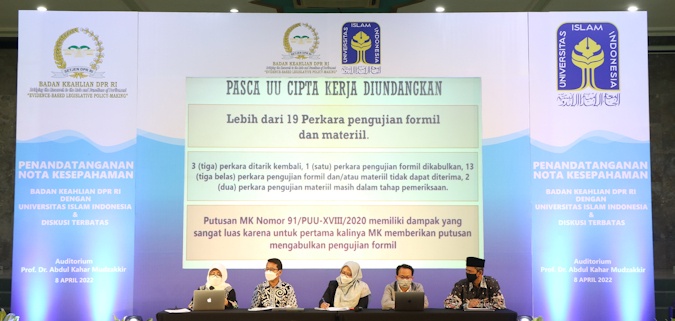Setiap perguruan tinggi merupakan entitas unik. Mereka lahir di ruang sejarah yang berbeda dan dibangun di atas kesadaran yang beragam, meski ada irisan di sana. Karenanya, mengandaikan keseragamaan untuk semuanya, merupakan sesuatu yang melawan fakta.
Hanya saja, di lapangan, kesadaran ini tidak mengemuka, atau paling tidak, bukan yang menggema. Selalu saja ada upaya untuk melihatnya secara serupa.
Ini adalah tantangan setiap perguruan tinggi untuk kembali melakukan refleksi secara kolektif. Termasuk di antaranya adalah untuk menemukan dan menegaskan kembali misi yang diembannya. Cara paling sederhana adalah menyelisik nilai-nilai yang diyakini dan ditanamkan oleh para pendirinya. Universitas Islam Indonesia (UII) pun tidak berbeda.
Dua kubu
Tantangan itu semakin nyata ketika ideologi baru merasuk dalam pengelolaan perguruan tinggi. Beragam predikat disematkan, mulai neoliberalisme, birokratisasi, sampai dengan korporatisasi. Semuanya mengandung makna yang dipercaya tidak sejalan dengan idealisme atau misi asasi kehadiran sebuah perguruan tinggi.
Setiap kubu punya pendukung dan penggemarnya, dengan argumentasinya masing-masing. Meski, keduanya pun punya irisan dalam praktik. Tentu, meja diskusi dapat dibuka. Inilah asyiknya dunia akademik, ketika beragam perspektif mendapatkan tempat untuk diungkap ke ruang publik.
Jika ingin disederhanakan, pembeda kedua kubu ini adalah pada basis nilai yang melandasi gerak. Manifestasinya adalah beragam praktik yang sampai level tertentu dapat melupakan perguruan tinggi dari misinya.
Kita ambil beberapa ilustrasi. Kubu neoliberal mengagungkan persaingan tanpa ampun, sedangkan kubu ideal, lebih menghargai persandingan alias kemitraan. Tidak jarang, atas nama persaingan, publik pun dimanipulasi dengan beragam informasi yang diglorifikasi. Etos kecendekiawanan pun tidak lagi mendapatkan perhatian cukup, asal peringkat perguruan tetap di pucuk. Edukasi publik seakan tidak mendapatkan tempat lagi.
Pengamal kubu neoliberal menikmati birokratisasi sebagai bos, sedang yang satunya mengedepankan semangat kolegial yang dianggap tidak modern atau bahkan tidak sejalan dengan kemajuan. Tidak jarang, pemimpin penganut kubu yang kedua, dianggap pemimpin lemah karena tidak mau memaksa.
Tentu, bagi penganut setiap kubu, serangkaian kilah dapat disampaikan. Inilah indahnya otak manusia yang mampu memproduksi beragam argumentasi. Apalagi praktik kedua kubu ini ini tidak mempunyai garis demarkasi yang selalu tegas dan tidak saling bebas (mutually exclusive) sepanjang masa. Setiap perguruan tinggi, bisa jadi menjalankan praktik kedua kubu, meski nilai pijakannya tidak kompatibel. Sebagian mendasarkan pada desain sadar, sedang yang lain karena kekangan yang tak bisa dihindari.
Pilihan berlabuh
UII akan berlabuh di kubu mana? Ini sebetulnya pilihan sederhana dari dua pilihan, tetapi mempunyai implikasi rumit yang tidak semua perguruan tinggi sanggup menerimanya. Berlabuh di kubu idealisme secara normatif benar dan sulit mencari yang tidak sepakat. Tetapi, jika pilihan ini berimbas pada peringkat perguruan tinggi dengan basis sistem metrik yang cenderung abai pada keunikan, misalnya, keraguan mulai menggelayut.
Idealisme yang menjaga semangat kolegialitas seringkali dianggap lambat dalam merespons perubahan. Keputusan kolektif seringkali dinilai terlalu banyak melibatkan kompromi politis dari begaram aktor yang terlibat. Sebaliknya, pendekatan korporat dipercaya akan menjadikan kampus semakin melesat, meski tidak jarang diikuti dengan penggadaian sebagian akal sehat.
Apa jalan keluarnya? Ada masanya, refleksi jujur perlu dilakukan secara kolektif dengan tabula rasa yang kalis kepentingan sesaat dan menggantikannya dengan nilai-nilai asasi. Jika ini dilakukan, akan muncul beragam jalan tengah yang disepakati bersama dan sekaligus disadari risikonya.
Namun ada syarat mutlak untuk dapat melakukan refleksi yang bermakna. Termasuk di antaranya adalah dengan tidak menjebakkan diri pada narasi publik. Independensi dalam bersikap memang tidak selalu nyaman, apalagi di tengah gempuran praktik neoliberalisme yang dianggap sebagai norma baru. Tidak hanya di kancah nasional maupun internasional, tetapi juga di dalam kampus sendiri.
Mari, lihat diskursus ini, sebagai sebuah dinamika yang perlu disyukuri. Diskusi dengan hati dingin harus terus dilakukan untuk merespons perubahan yang tak henti dengan tetap merawat misi. Semoga Allah senantiasa memudahkan UII.
Tulisan ini sudah dimuat di UIINews ediri April 2022.