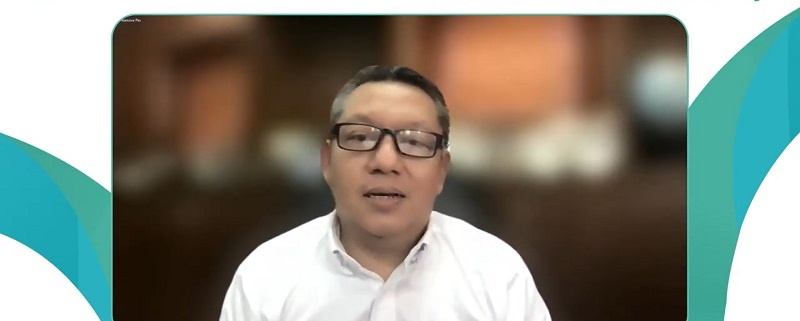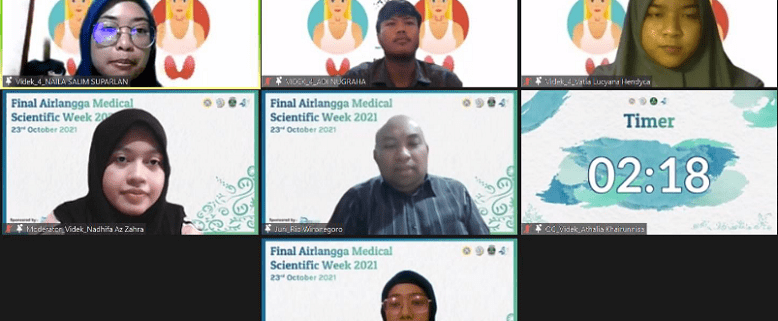Alhamdulillah. Saya bersyukur dan berbahagia, Bapak Dr. Sukidi di sela-sela kesibukan, berkenan meluangkan waktu untuk berbagi perspektif di Universitas Islam Indonesia dalam kuliah umum.
Tema yang diangkat dalam kuliah umum ini adalah Visi Islam Baru untuk Indonesia Maju. Tema yang menurut saya, sangat progresif untuk menghadirkan Islam yang kontekstual dan menjadi bagian solusi bangsa ini. DI sinilah Islam akan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dan, bukan sebaliknya, Islam justru berpotensi menjadi bagian masalah, karena ulah pemeluknya.
Selain itu, tema ini juga mengindikasikan bahwa tidak ada pertentangan antara semangat keislaman dan kebangsaan. Ini sejalah dengan komitmen yang ditanamkan oleh para pendiri UII yang berasal dari lintasorganisasi dan latar belakang, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII), Perikatan Umat Islam (PUI), dan para tokoh bangsa lain.
Dua semangat tersebut terangkum dalam nama UII, yang dalam bahasa Arab menjadi Al-jami’ah Al-islamiyyah Al-indunisiyyah, Universitas Islami Indonesiawi. Pembacaan Al-Qur’an dan lagu Indonesia Raya di awal acara ini merupakan simbol dua komitmen ini.
Selain itu, UII adalah rumah besar untuk keragaman pemikiran Islam yang disatukan dengan semangat kebangsaan.
Izinkan saya berbagi beberapa perspektif dalam sambutan pembukaan singkat ini.
Permusuhan sosial atas nama agama
Pertama, Pew Research Center pada akhir September 2021 menyajikan sebuah laporan terkait dengan permusuhan sosial (social hostilities) atas nama agama, apapun namanya. Permusuhan sosial dapat berupa kekerasan terhadap identitas agama seseorang, sampai dengan konflik sektarian dan terorisme. Laporan didasarkan pada analisis 198 negara. Pada 2019, permusuhan sosial yang tinggi atau sangat tinggi (skor 3,6 atau lebih tinggi) berdasar Social Hostilities Index (SHI) “hanya” terjadi di 43 negara, menurun dibandingkan dengan 2017 (56) dan 2018 (53).
Ini tentu kabar baik yang perlu disyukuri. Nampaknya semua yang hadir di sini tidak sulit untuk bersepakat, permusuhan atas nama agama, apapun agamanya, tidak bisa kita terima. Kita yakin, nilai-nilai perenial agama justru seharusnya, membawa manusia kepada kebaikan, sikap saling menghormati, dan perdamaian. Jika ada sebagian kecil pemeluk agama yang cenderung kepada permusuhan itu adalah fakta sosial, dan hal itu bisa terjadi di semua agama. Tetapi, itu bukan dasar yang valid untuk melakukan generalisasi yang membabi buta.
Curiga tak berkesudahan
Kedua, fakta sosial lain yang kita temukan adalah sebagian orang mempunyai perspektif yang berbeda dengan yang dibayangkan kelompok lain. Ada banyak data yang bisa ditampilkan, termasuk yang terserak di media massa, buku, halaman jurnal ilmiah, atau bahkan dalam film Holywood.
Huntington (1996) dalam bukunya The Clash of Civilization yang terkenal itu, misalnya, mengasosiasikan Islam dengan “jeroan berdarah” (“bloody innards”) atau “batas-batas berdarah” (“bloody borders”). Atau, Said (1979) dalam bukunya Orientalism telah memberikan gambaran bagaimana media Barat membangun opini terkait dengan Islam, yang tidak selalu menggembirakan.
Tokoh dalam film Hollywood yang dibingkasi dengan terorisme, hampir selalu berwajah atau bernama Arab, yang dengan mudah diasosiasikan dengan agama tertentu. Tidak sulit menemukan contohnya, seperti London has Fallen, True Lies, Eye in the Sky, dan masih banyak lagi.
Survei yang dilakukan oleh Pew Research Center (Lipka, 2017) memberikan gambaran lebih mutakhir bagaimana atribusi yang cenderung negatif terhadap kelompok yang berbeda itu nyata adanya. Survei yang dilakukan di negara-negara dengan pemeluk Islam mayoritas menemukan bagaimana orang Barat dipersepsikan. Mereka dianggap (mulai dari yang paling dominan) egois, brutal, rakus, amoral, arogan, dan fanatik. Ini adalah kombinasi sempurna semua keburukan.
Sebaliknya, orang Barat memberikan atribusi berikut kepada muslim: fanatik, jujur, brutal, dermawan, arogan, dan egois. Kombinasi atribut yang tidak lazim dan sulit dibayangkan untuk menyatu dengan harmoni.
Pertanyaannya: apakah memang seperti ini di lapangan? Mereka yang pernah hidup di “dua alam” (negeri Barat dan muslim) sangat mungkin akan memberi perspektif yang berbeda. Di sisi lain, dialog sehat dan jujur nampaknya memang menjadi pekerjaan rumah bersama.
Islam dan konflik
Ketiga, untuk menyelisik lebih jauh, peneliti dari Peace Research Institute di Oslo (PRIO), Gleditsch dan Rudolfsen (2016), memunculkan pertanyaan besar: apakah negara-negara muslim lebih rentan terhadap kekerasan? Data yang mereka kumpulkan dari 1946-2014 menunjukkan bahwa dari 49 negara yang mayoritas penduduknya muslim, 20 (atau 41%) di antaranya mengalami perang sipil (perang sesama anak bangsa), dengan total durasi perang 174 tahun atau sekitar 7% dari total umur kumulatif semua negara tersebut (2,467 tahun).
Pasca Perang Dingin, sebagian besar perang adalah perang sipil dan proporsi terbesar terjadi di negara-negara muslim. Bukan hanya karena perang sipil di negara-negara muslim meningkat, tetapi juga karena konflik di negara lain berkurang. Fakta yang lebih dari cukup untuk mencelikkan mata kita.
Tentu catatan optimis masih ada. Empat dari lima negara dengan penduduk muslim terbesar, tidak terjebak dalam perang sipil. Indonesia salah satunya. Tiga yang lain adalah India, Bangladesh, dan Mesir.
Bahwa ajarah Islam tidak mempunyai korelasi dengan konflik juga diamini oleh Fuller (2010), mantan pentolan CIA, yang terekam dalam bukunya A World without Islam. Secara hipotetik, dalam sebuah diskusi di Rumi Forum, sebuah lembaga yang didirikan di Washington DC untuk dialog antaragama dan antarbudaya, Fuller menyatakan ”bahkan jika Islam dan Nabi Muhammad tidak pernah ada, hubungan antara Barat, terutama Amerika Serikat, dan Timur Tengah tidak akan berbeda jauh”.
Dalam bahasa lain yang lebih sederhana, “jika Islam tidak ada, konflik di muka bumi pun masih terjadi”.
Revitalisasi peran agama
Karenanya, merevitalisasi peran agama saat ini menjadi semakin penting, ketika fakta di lapangan memerlukan penjelasan yang lebih canggih. Survei yang dilakukan Pew Research Center pada pertengahan 2020 (Tamir et al., 2020) menemukan bahwa negara yang warganya mempunyai kepercayaan tinggi terhadap Tuhan, justru mempunyai Produk Domestik Bruto per kapita yang rendah.
Indonesia termasuk negara yang warganya sangat percaya dengan Tuhan, tetapi menempati posisi 102 negara paling korup dari 180 negara menurut Tranparency International. Belum lagi ditambah fakta kecenderungan global, proporsi terbesar mereka yang tidak percaya kepada Tuhan adalah yang berpenghasilan lebih besar, berpendidikan lebih tinggi, dan berusia lebih muda. Pew Research Center menyebut fakta ini sebagai The Global God Divide, kesenjangan Tuhan global.
Ajaran Islam seharusnya bisa menjadi pijakan dan katalis yang mendorong kemajuan Indonesia. Dan, muslim sudah seharusnya menjadi lokomotif dan aktor utamanya.
Referensi
Fuller, G. E. (2010). A World without Islam. New York: Little, Brown and Company.
Gleditsch, N. P., & Rudolfsen, I. (2016). Are Muslim countries more prone to violence?. Research & Politics, 3(2), 1–9
Lipka, M. (2017). Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world. Tersedia daring di https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/
Majumdar, S. (2021). Key findings about restrictions on religion around the world in 2019. Tersedia daring di https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/09/30/key-findings-about-restrictions-on-religion-around-the-world-in-2019/
Tamir, C., Connaughton, A. & Salazar, A. M. (2020). The Global God Divide. Tersedia daring di https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/
Sambutan pembuka Kuliah Umum Visi Baru Islam untuk Indonesia Maju oleh Sukidi, Ph.D. di Universitas Islam Indonesia, 30 Oktober 2021.