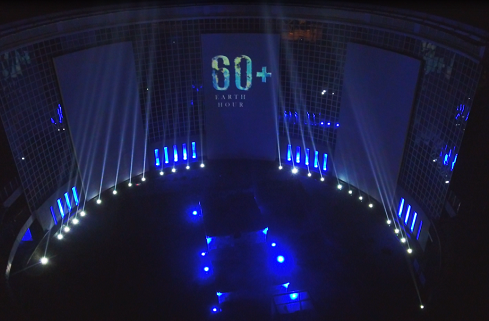Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 merupakan bagian dari ritual bangsa dalam merawat demokrasi di Indonesia. Dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di muka bumi. Pelaksanaan pemilu secara serentak untuk pertama kalinya guna memilih pasangan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten/kota, telah memunculkan harapan dan sekaligus tantangan tersendiri.
Pemilu adalah salah satu ikhitar menjaga legitimasi yang terpilih. Legitimasi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, berkaca dari cerita belahan dunia lain, kita sebagai bangsa, harus secara bersama-sama mengawal kualitas proses. Kebocoran dalam proses akan sangat mungkin meningkatkan ketidakpercayaan warga, dan ujungnya adalah rendahnya legimitasi yang terpilih.
Untuk memberikan ilustasi, pada September 2016, CNN[1] menurunkan laporan dari Afrobarometer (afrobarometer.org), sebuah institut riset lintas Afrika tentang rendahnya kepercayaan terhadap pemilu. Hanya sebanyak 44% warga Afrika yang menjadi responden di 36 negara yang percaya dengan pemilu. Sebabnya beragam. Suap, intimidasi, dan korupsi adalah beberapa alasan di belakang rendahnya kepercayaan terhadap pemilu. Sebanyak 51% responden bahkan tidak percaya dengan Komisi Pemilihan Umum di sana. Potret ini semakin buram karena sekitar 70% responden mengaku pernah ditawari “suap” untuk memilih calon tertentu.
Tentu, kita tidak ingin, potret buram ini terjadi di Indonesia. Harapan terhadap hadirnya pemilu yang damai adalah anti-tesis dari temuan Afrobarometer tersebut.
Potensi kebocoran proses dengan segala bentuknya dalam pemilu selalu ada. Konteks Indonesia tidak terlepas dari potensi itu. Apalagi, pada saat ini ketika teknologi informasi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemilu, termasuk ketika musim kampanye. Sisi buram teknologi informasi dapat dieksploitasi untuk kepentingan jangka pendek oleh mereka yang ‘gelap mata’.
Penggunaan teknologi untuk mempengaruhi hasil pemilu dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016 telah menjadi pencelik mata. Pemilu saat ini nampaknya tidak lagi menjadi pesta demokrasi warga negara saja, tetapi juga berpotensi menarik negara asing untuk terlibat dengan kepentingannya masing-masing. Laporan yang diturunkan oleh Majalah Foreign Affairs[2] membahas tentang pemilu yang tidak bisa diretas (the unhackable election).
Laporan memberikan gambaran bagaimana penggunaan teknologi informasi dapat memfasilitasi “kecurangan” pemilu. Bahkan negara asing bisa ikut “nimbrung” (meddle) di dalamnya. Selain pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2016, pemilihan Presiden Prancis 2017, pemilu Italia pada Maret 2018, referendum di Macedonia pada September 2018, pemilu Swedia pada September 2018, dan pemilu Bosnia dan Herzegowina pada Okober 2018, diduga kuat diwarnai dengan “campur tangan” asing melalui penyampaian informasi tertentu (terutama hoaks) dengan upaya terstruktur. Meskipun, sebagaimana dilaporkan oleh Majalah Foreign Affairs, negara-negara tersebut menyangkal adanya “campur tangan” asing.
Sosial media menjadi senjata andalan. Salah satu indikasinya adalah cacah akun palsu media sosial, termasuk Twitter, Facebook, dan Instagram, meningkat tajam mendekati hari-H. Penyebaran konten melalui medis sosial juga tidak jarang menggunakan robot.
Apakah ada penggunaan robot dalam penyebaran informasi pada media sosial di Indonesia? Jawaban singkatnya: ada, dan bisa membuktikan. Ketika ada informasi yang sama dibagi di media sosial dari beragam akun tetapi pada waktu yang sama, sangat patut diduga, bahwa itu di luar kemampuan manusia.
Bagaimana di Indonesia? Meskipun sulit membuktikan “campur tangan” asing, namun berkaca dari kejadian di negara lain yang disebut di atas tadi, secara teoretis, peluang itu ada. Jika ini terjadi dengan bukti nyata, tentu akan sangat mempengaruhi legimitasi hasil pemilu. Siapapun pemenangnya.
Terlepas dari itu, perang pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden di media sosial, sampai saat ini sudah sampai pada tarap yang tidak sehat. Beragam ujaran kebencian dan anti-kedamaian telah menjadi menu sehari-hari dan sudah membudaya. Berita bohong (hoaks) pun tidak sulit ditemukan.
Jika budaya ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat membahayakan persatuan bangsa. Saat ini, di dunia maya, tidak sulit untuk melihat munculnya polarisasi sosial yang sangat akut. Konflik di dunia maya pun dapat berkembang menjadi konflik di dunia nyata. Sebagian pendukung buta pasangan calon nampaknya telah menjelma menjadi komunitas masokhis sosial yang tuna empati, menikmati kebencian dan penderitaan orang lain. Jika hal ini terus terjadi dan bahkan bereskalasi, pemilu yang damai dan bermartabat akan menjadi taruhan mahal.
Jika memang kebencian itu tidak bisa dihilangkan, pesan Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang disampaikan sekitar 14 abad lalu, yang terekam dalam Kitab Nahjul Balaghah, nampaknya masih relevan untuk dijadikan pedoman:
“Cintailah kekasihmu itu sekedarnya saja, boleh jadi kamu akan membencinya suatu ketika. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja, boleh jadi kamu akan mencintainya suatu ketika”
Mari, menjadi pemilih yang mandiri dan mengedepankan akal sehat. Waspadai upaya dari pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi pemilu dan kemungkinan campur tangan asing.
Kita bersama berdoa, semoga pemilu segera berlalu dengan berkualitas, menghasilkan orang-orang terpilih dengan legitimasi tinggi. Semoga bangsa Indonesia kembali waras dan tidak membocorkan energi yang terbatas, untuk sesuatu yang tidak berdampak untuk kemajuan bangsa.
Disarikan dari sambutan Rektor Universitas Islam Indonesia dalam pembukaan Seminar Nasional “Mendorong Pemilu Damai dan Substantif: Peta Jalan Menuju Perlindungan Hak Memilih” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) pada 28 Maret 2019.
[1] https://edition.cnn.com/2016/09/25/africa/africa-view-election-distrust/index.html
[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-12-11/unhackable-election