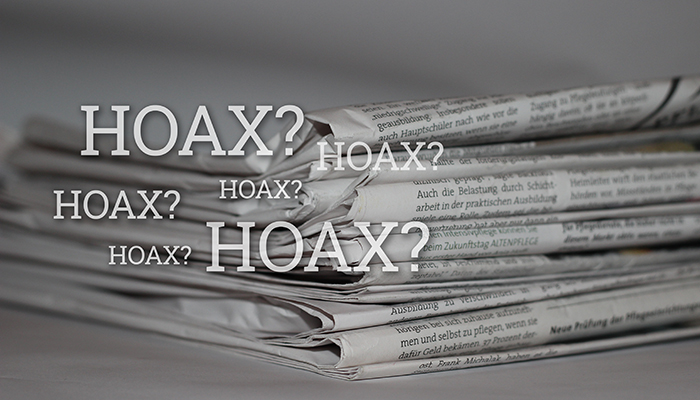 Bangsa Indonesia sebentar lagi menghelat pemilihan presiden yang dibarengkan dengan pemilihan legislatif pada April 2019. Hari ini, suasana persiapan pesta sudah terasa hangat.
Bangsa Indonesia sebentar lagi menghelat pemilihan presiden yang dibarengkan dengan pemilihan legislatif pada April 2019. Hari ini, suasana persiapan pesta sudah terasa hangat.
Pesta demokrasi empattahunan ini , di sisi sangat strategis untuk menghasilkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang berkualitas negarawan, tetapi di sisi lain, ekses dari pesta yang tidak sehat dapat menggurat luka sangat dalam bagi yang belum dewasa dalam berpolitik.
Saya yakin, semua sepakat bahwa sisi gelap pesta demokrasi ini harus kita hindarkan, supaya bangsa ini tidak semakin menyia-nyiakan energi positifnya untuk aktivitas yang tanpa dampak. Termasuk dalam penyia-nyian energi bangsa adalah praktik penyebaran hasutan dan ujaran kebencian yang tiada berbatas. Informasi plintiran dan bahkan bohong (hoaks) diproduksi untuk kepentingan jangan pendek tanpa mempedulikan rajutan keragaman bangsa.
Kepemimpinan profetik yang dilandasi teladan Rasulullah, bagi saya, selain membahas kualitas pribadinya, seharusnya tidak mengabaikan sikap pribadi (standpoint) untuk beragam isu penting bangsa.
Dalam tulisan ini, saya ingin mengangkat satu topik yang seharusnya menjadi perhatian para pemimpin dan calon pemimpin bangsa ini karena statusnya yang sudah akut dan kritis, yaitu terkait dengan penyebaran hoaks.
Mengapa isu ini menjadi penting? Pengalaman lampau kita mengajarkan bahwa dalam musim pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, produksi hoaks meningkat tajam. Tidak jarang, meski sering dielak, hoaks menjadi bagian strategi pemenangan dan menhinakan lawan. Bisa jadi tim kampanye formal tidak menuliskan ini dalam daftar strateginya, tetapi sikap tegas terhadap penyebaran hoaks seringkali bersifat ambigu dan abu-abu.
Seyogyanyalah, bukan karena hoaks yang menyebar menguntungkan diri atau jagonya, maka kemudian mata seakan buta. Bukan karena hoaks yang bersliweran menghinakan lawannya, telinga seakan tuli. Juga, bukan karena hoaks tidak mengganggu dirinya, hati menjadi mati.
Kepemimpinan profetik juga seharusnya tidak menutup mata terhadap pendukungnya yang mengabaikan nilai-nilai universal kemanusiaan, seperti kejujuran dan kedamaian; sesuatu yang seringkali sulit ditampik dalam pemenangan kontestasi politik. Kualitas pendukung pemuja hasutan dan anti stabilitas sosial, selama menguntungkan dirinya, lantas tidak ditegur dan diarahkan. Sikap yang tegas tidak diberikan. Sikap seperti ini tentu jauh dari kualitas pemimpin yang mengusung nilai-nilai kenabian, kepemimpinan profetik.
Mari sejenak kita kupas beragam aspek terkait dengan hoaks dan penyebarannya.
Pertama, mengapa kita (manusia) menyebar hoaks? Riset menunjukkan bahwa banyak keputusan yang kita ambil, seringkali bukan karena rasionalitas individu, tapi berdasar narasi kelompok. Di sini, kredibilitas sumber sangat mempengaruhi interpretasi sosial atas informasi. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa kita adalah pencari informasi yang bias; kita mencari informasi yang mendukung pandangan kita dan mengabaikan informasi yang berseberangan. Karenanya, membetulkan informasi yang salah tidak serta merta mengubah kepercayaan orang. Hasilnya adalah kamar gema, ketika informasi senada berulang dan beredar di kalangan tertutup. Di sini, biasanya terjadi eksposur terpilih terhadap informasi yang beredar dan bias konfirmasi karena kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung pemahaman sebelumnya.
Kedua, bagaimana hoaks menyebar? Fitur berbagi sosial media merupakan sumber kuat penyebar hoaks. Proses berbagi ini dapat dilakukan oleh pegiat media sosial atau bot, program yang ditujukan untuk maksud serupa. Media sosial yang difasilitasi Internet telah menghadirkan kekayaan informasi di satu sisi, memunculkan kemiskinan atensi individu atas informasi di sisi lainnya. Hal ini, sampai tingkat tertentu, akan mencegah pemilahan informasi berdasar kualitas. Informasi berkualitas rendah dan tinggi sama-sama dapat menyebar dengan cepat.
Biasanya, informasi, baik hoaks atau fakta, menjadi viral tidak melalui rangkaian pertukaran informasi yang panjang antarpengguna-biasa. Dalam konteks ini, media, pesohor, atau tokoh dengan banyak pengikut dapat menyebar informasi dengan jangkauan luas memperpendek rangkaian.
Ketiga, siapa penyebar hoaks? Hoaks dapat disebar oleh beragam aktor: individu, organisasi bermotivasi finansial/politis, atau bahkan pemerintah/negara. Kita dapat menjadi penyebar hoaks ketika ‘ringan jari’ dalam membagi informasi tanpa verifikasi. Partai politik dan simpatisannya juga tidak kalis dari potensi menjadi pelaku jika menghalalkan semua cara dalam memenangkan kontestasi. Ketika pemerintah memberikan informasi yang menutupi fakta yang ada, tidak sulit menyatakan bahwa mereka juga dalam golongan ini.
Keempat, mengapa kita percaya atau tidak hoaks? Setiap dari kita mempunyai pandangan dunia yang berdasar pada konsep, kepercayaan, dan pengalaman, untuk menginterprstasikan dan menilai realitas. Jika hoaks yang kita terima sesuai dengan pandangan dunia kita, maka kita akan cenderung percaya dengan hoaks tersebut. Persepsi terhadap ancaman yang muncul karena hoaks juga mempengaruhi tingkat kepercayaan kita. Jika hoaks tersebut menimbulkan potensi masalah yang berdampak kepada kita, tidak jarang kita mudah mempercayainya. Repetisi kemunculan hoaks atau frekuensi kita berjumpa dengan hoaks serupa juga memicu tingkat kepercayaan.
Kelima, apa dampak hoaks? Beragam dampak hoaks dapat diidentifikasi dengan mudah. Segregasi atau polarisasi sosial adalah salah satunya. Tidak sulit mencari ilustrasi kasus ini di seputar musim pemilihan kepala daerah. Sialnya, polarisasi ini juga terbawa ke dunia nyata. Dampak buruk lain adalah terbentuknya masyakarat masokhis tuna empati yang cenderung sarkastik dan menikmati penderitaan orang lain. Ujungnya adalah tertutupnya manfaat media sosial.
Keenam, apa yang bisa kita lakukan untuk menghalau hoaks? Biasakan menjadi manusia yang berpikiran terbuka dan terlatih dalam diskusi yang dilandasi fakta. Pendekatan ilmiah berbasis data tanpa bias diperlukan. Selain itu, suarakan kebenaran dengan lebih lantang. Di sini, publik perlu diedukasi untuk membentuk ‘ketahanan informasi’, bersikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima, tidak menelannya mentah-mentah, dan tidak asal menyebarkannya. Pemahaman dan keataan atas nilai-nilai kemanusiaan universal yang dibawa oleh norma agama juga menjadi sangat penting. Ini adalah rem paling pakem. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan umatnya untuk menyebar kebencian dan berperilaku anti kedamaian dengan menyebar hoaks.
Mari, perlebar perspektif dan perpanjang horison kemanusiaan kita. Bisa jadi saat ini, kita diam melihat hoaks mengoyak tenun kebangsaan kita. Atau, bahkan menjadi bagian gerombolan penyebar tanpa merasa bersalah. Tapi kita perlu ingat, bisa jadi, kita pun dapat menjadi korban dari hoaks.
Tentu, mengambil sikap hanya ketika menjadi korban adalah pilihan pengecut dan mementingkan diri sendiri. Sikap seharusnya, bukan karena kita dapat apa atau terkena dampak, tetapi didasarkan pada nilai-nilai kebajikan abadi yang anti penyebaran hasutan dana kebencian.
Jika kebencian itu masih ada, sebagian orang mengatakan itu sangat manusiawi. Tapi, mari upayakan tidak menujukan kebencian kepada pribadi tetapi kepada gagasan atau program. Kalau kata kebencian tetap dipertahakankan, mari berikan sifat untuknya manjadi “kebencian yang akademik”. Ada adu argumen di sana. Ada tukar gagasan cerdas di dalamnya. Jika sintesis masih belum terlaksana, atsar Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang terekam dengan indah dalam Kitab Nahjul Balaghah dapat menjadi benteng terakhir:
“Cintailah kekasihmu itu sekedarnya saja, boleh jadi kamu akan membencinya suatu ketika. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja, boleh jadi kamu akan mencintainya suatu ketika”
——
Disarikan dari Pidato Kunci pada Seminar Nasional “Kepemimpinan Profetik” yang diselenggarkan pada 13 September 2018







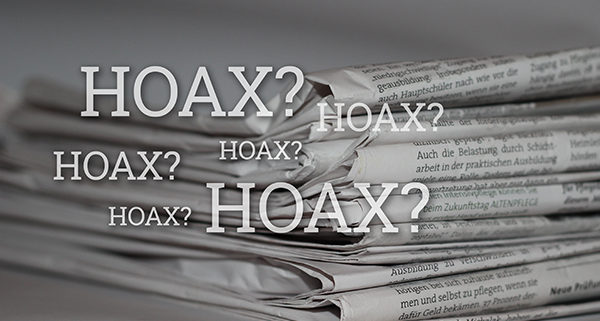
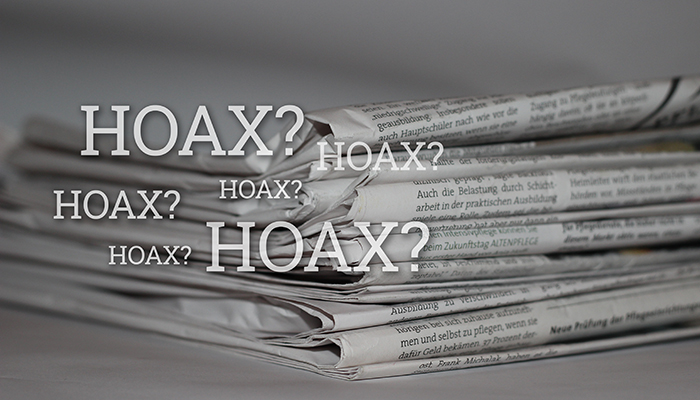 Bangsa Indonesia sebentar lagi menghelat pemilihan presiden yang dibarengkan dengan pemilihan legislatif pada April 2019. Hari ini, suasana persiapan pesta sudah terasa hangat.
Bangsa Indonesia sebentar lagi menghelat pemilihan presiden yang dibarengkan dengan pemilihan legislatif pada April 2019. Hari ini, suasana persiapan pesta sudah terasa hangat.



